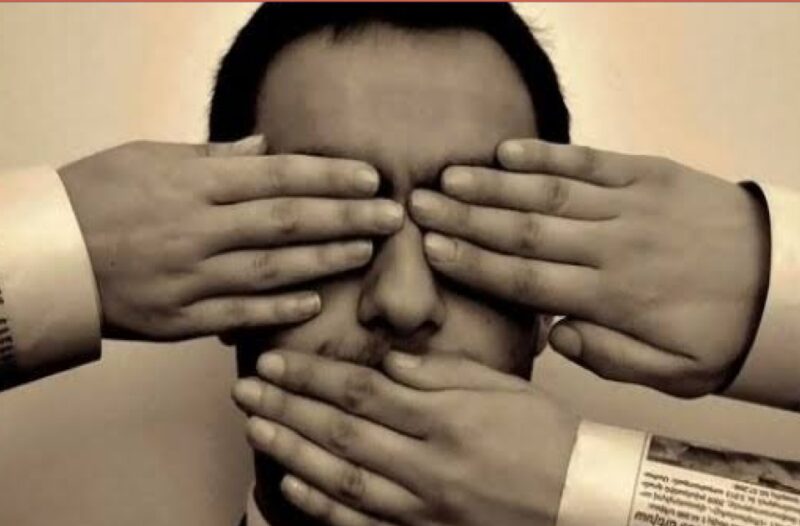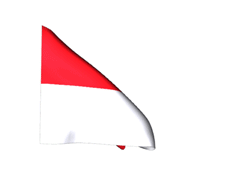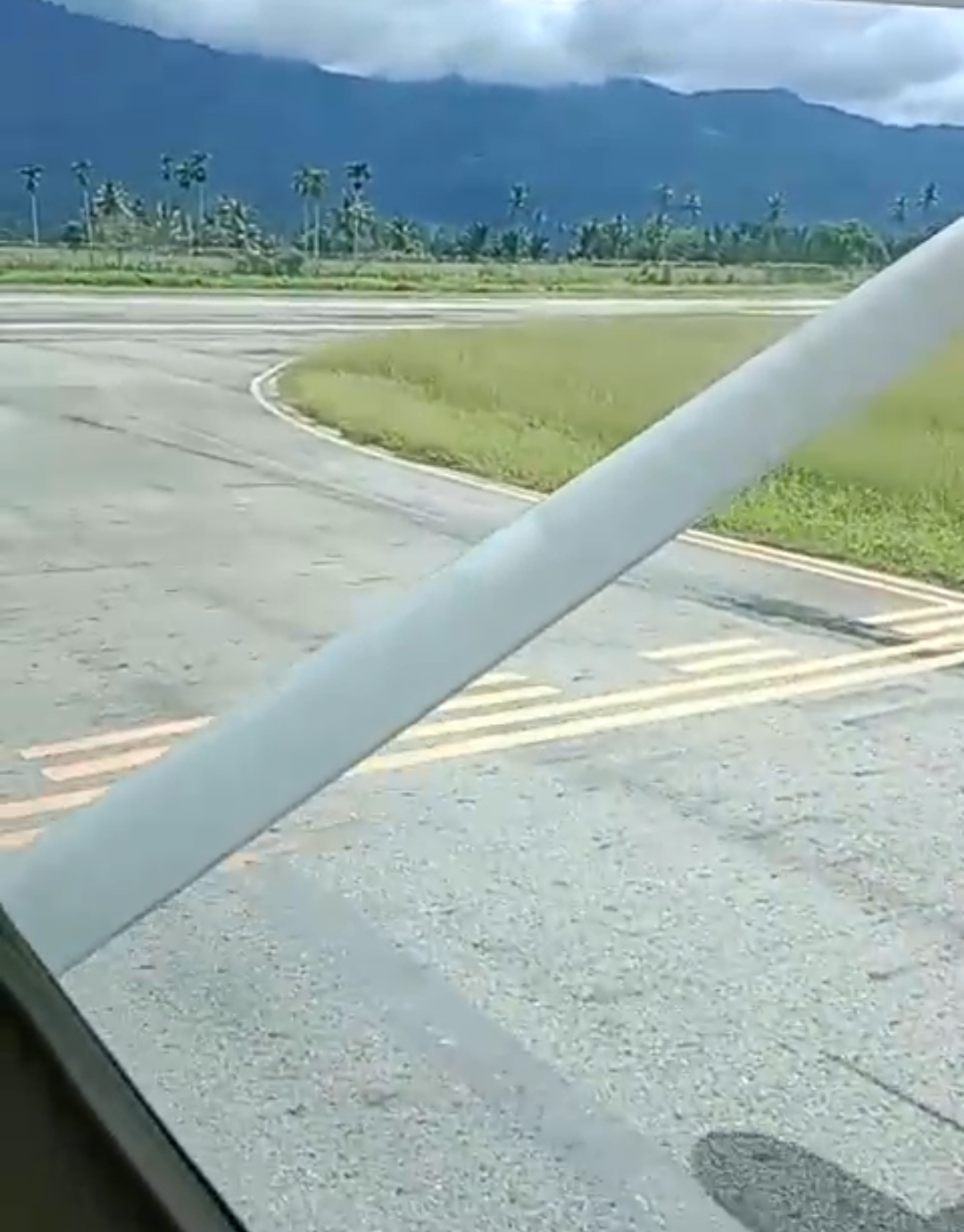Photo Ilustrasi
Jakarta – Di tengah hiruk pikuk informasi, sebuah suara keras kembali menggema, mempertanyakan otoritas yang diklaim sebagai penjaga gawang pers nasional: Dewan Pers.
Bukan sekadar kritik biasa, ini adalah gugatan terhadap apa yang disebut sebagai “pembodohan publik yang dilembagakan” melalui praktik verifikasi media.
Kali ini, sorotan tajam datang dari Wilson Lalengke, tokoh pers nasional yang juga Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), yang tak segan menyebut praktik ini sebagai pelanggaran undang-undang dan pembungkaman kebebasan pers.
Wilson Lalengke tidak beretorika kosong. Ia menunjuk langsung Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 15, yang secara eksplisit tidak memberikan mandat kepada Dewan Pers untuk memverifikasi media secara nasional.
“Dewan Pers hanya bertugas mendorong kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Tidak ada satu pun ayat yang memberi mereka kewenangan untuk memverifikasi media secara nasional, apalagi dijadikan alat pembatas akses informasi,” tegas Wilson, seolah menelanjangi praktik yang dinilai melampaui batas kewenangan.
“Pembodohan publik yang dilembagakan” menjadi frasa kunci yang menggambarkan betapa fatalnya dampak praktik ini. Ketika pemerintah daerah, kementerian, bahkan institusi penegak hukum menjadikan status verifikasi Dewan Pers sebagai syarat mutlak untuk kerja sama atau akses liputan, diskriminasi terhadap media non-terverifikasi menjadi tak terhindarkan.
Mereka tidak diundang konferensi pers, bahkan diintimidasi. Ini bukan lagi soal profesionalisme, melainkan monopoli informasi dan pembungkaman suara-suara independen.
Ironisnya, alasan Dewan Pers untuk menjaga standar profesionalisme dan integritas jurnalistik justru membuka pintu bagi oligarki pers. Bahkan, Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digagas di bawah otoritas Dewan Pers pun dinilai cacat hukum. “Semua uji kompetensi profesi diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan harus berada di bawah pengawasan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Jadi, UKW oleh Dewan Pers itu ilegal secara sistem sertifikasi nasional,” jelas Wilson, membongkar kelemahan fundamental dalam sistem yang dibangun.
Tak hanya itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013 menjadi landasan hukum yang tak terbantahkan. Putusan ini dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi media atau wartawan untuk bergabung ke organisasi pers atau harus terverifikasi Dewan Pers.
Ini adalah tamparan keras bagi praktik-praktik yang membatasi kerja jurnalistik hanya pada segelintir media yang “sah” menurut kriteria Dewan Pers.
Kriminalisasi terhadap wartawan dari media tidak terverifikasi dengan pasal karet seperti pencemaran nama baik menjadi bukti nyata bahwa perlindungan hukum menjadi relatif, tergantung status verifikasi.
“Kalau negara tunduk pada lembaga non-pemerintah seperti Dewan Pers, ini jadi lucu. Pemerintah dan institusi hukum justru harus melindungi semua jurnalis, bukan hanya yang sudah disertifikasi oleh kelompok tertentu,” kritik Wilson, menunjukkan betapa carut-marutnya penegakan hukum dalam konteks pers.
Polemik ini bukan sekadar perdebatan hukum, melainkan pertarungan sengit antara kebebasan pers dan potensi monopoli kewenangan. Ketika negara membiarkan pembentukan oligarki pers yang membungkam media independen, maka kebebasan berekspresi akan terenggut.
“Ini bukan lagi sekadar perdebatan hukum. Ini tentang melawan pembodohan publik yang dilembagakan atas nama profesionalisme, yang sebenarnya justru membungkam keragaman suara dan kritik,” pungkas Wilson Lalengke.
Pesannya jelas: Verifikasi Dewan Pers hanyalah opsi, bukan syarat mutlak sahnya sebuah media.
Jika negara dan institusi terus menjadikan verifikasi sebagai syarat, maka itu bukan hanya kekeliruan administratif, melainkan pembodohan publik yang sistematis dan terlembaga.
Sampai kapan kita membiarkan kebebasan pers kita dibelenggu atas nama “profesionalisme” yang sepihak?. []