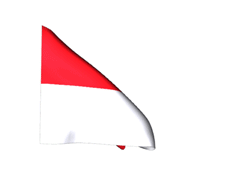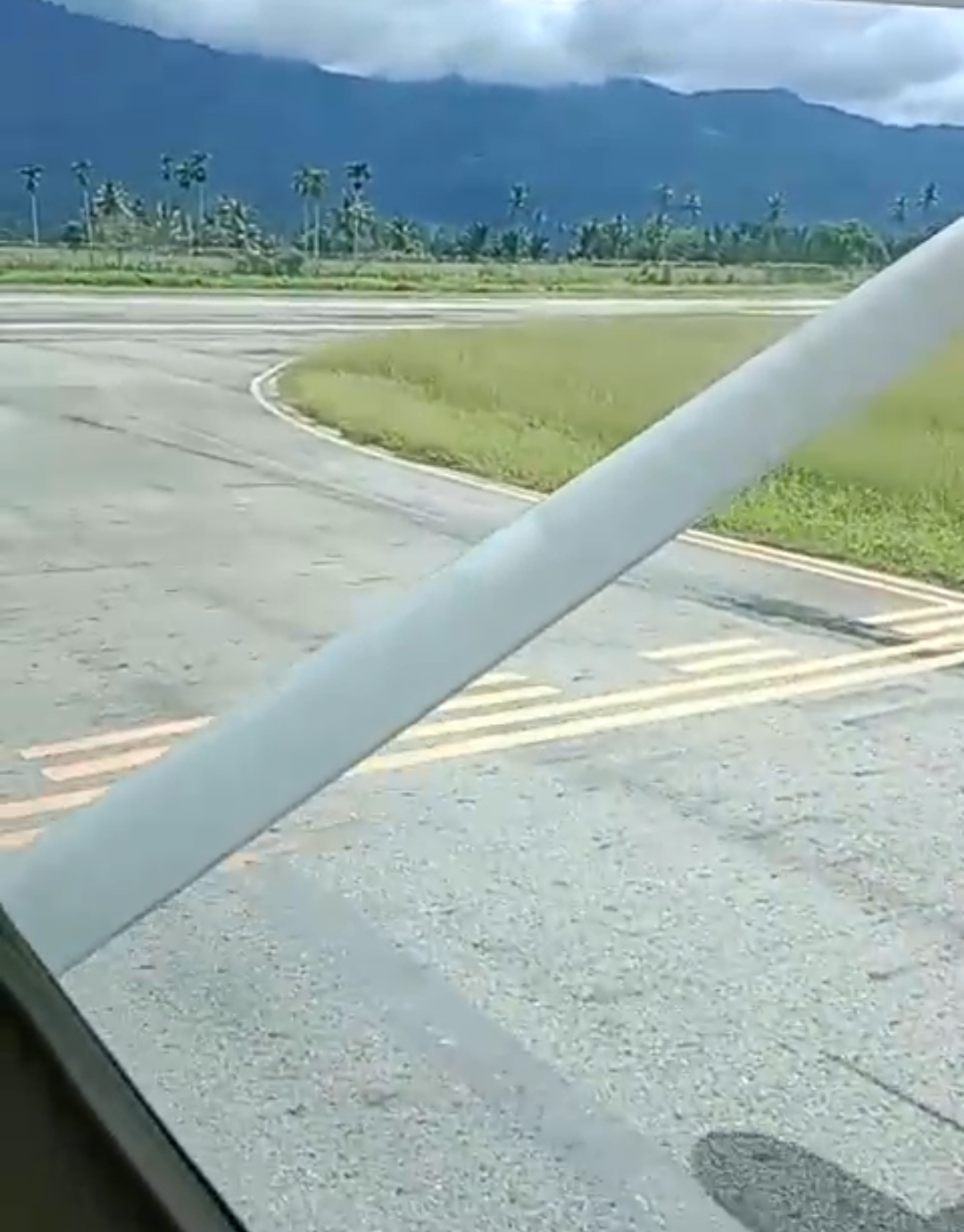Aceh Utara — Air datang bukan dari langit semata. Ia mengalir dari hutan yang dibuka, bukit yang dikeruk, dan izin yang diteken tanpa peduli akibat. Banjir besar Aceh Utara kini dipersoalkan sebagai kejahatan lingkungan hidup, bukan musibah.
Pandangan itu mengemuka di Pengadilan Negeri Lhoksukon, ketika masyarakat Aceh Utara menggugat korporasi-korporasi besar dengan tuntutan ganti rugi Rp100 triliun. Gugatan itu disebabkan banjir sebagai konsekuensi langsung dari eksploitasi sumber daya alam yang disengaja, terstruktur, dan dibiarkan berlangsung bertahun-tahun.
“Hutan dihancurkan. Daya dukung lingkungan dilanggar. Nyawa rakyat jadi ongkos,” kata Rius, kuasa hukum penggugat. “Ini bukan takdir. Ini kejahatan.” Kamis 29 Januari 2026.
Gugatan tersebut mendudukkan banjir sebagai hasil kebijakan dan aktivitas bisnis, bukan peristiwa alam yang netral. Dalam berkas perkara, penggugat merujuk Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara tegas melarang perusakan lingkungan dan mewajibkan pelaku menanggung seluruh akibatnya.
Investigasi lapangan pascabanjir menemukan pola yang berulang: pembukaan hutan secara masif, perubahan bentang alam, eksploitasi kawasan tanpa kendali, serta pembiaran pelanggaran lingkungan oleh otoritas. Hutan kehilangan fungsi ekologisnya. Sungai kehilangan penyangga. Air kehilangan jalur. Rakyat kehilangan rumah—bahkan nyawa.
Dalam hukum lingkungan, dalih izin tidak membebaskan tanggung jawab. Prinsip strict liability dalam Pasal 88 UU 32/2009 menempatkan korporasi sebagai penanggung jawab mutlak atas kerugian yang timbul dari kegiatannya, tanpa perlu pembuktian kesalahan.
“Izin bukan karpet merah untuk merusak lingkungan,” ujar Rius. “Ketika usaha menghasilkan bencana, tanggung jawab melekat otomatis.”
Tuntutan Rp100 triliun mencakup kehancuran rumah dan harta benda warga, lumpuhnya fasilitas publik, kerugian ekonomi kolektif, trauma sosial berkepanjangan, hingga korban jiwa. Gugatan ini berdiri di atas prinsip polluter pays: pencemar wajib membayar seluruh dampak yang ditimbulkannya, tanpa tawar-menawar.
Kuasa hukum penggugat Marhaban Adam, didampingi tim hukum Bencana Alam Sumatra Aceh yang dikenal sebagai Advokat Sagitarius, S.H., menegaskan perkara ini tidak membutuhkan pembuktian niat jahat. “Dalam hukum lingkungan, kerusakan adalah bukti. Korban adalah saksi. Selebihnya adalah tanggung jawab,” katanya.
Sikap korporasi justru memperkuat tudingan itu. Sejumlah perusahaan mangkir dari sidang perdana. Bagi penggugat, ketidakhadiran tersebut mencerminkan arogansi lama: merasa kebal hukum, terbiasa lolos dari akibat, dan jauh dari penderitaan warga di hilir.
Berdasarkan data Pengadilan Negeri Lhoksukon, delapan korporasi digugat: PT Linge Mineral Resources, PT Rajawali Telekomunikasi Selular, PT Woyla Aceh Minerals, PT Aceh Nusa Indrapuri, PT Aloer Timur, PT Tusam Hutan Lestari, PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, dan PT Golden Agri Resources (GAR) VIII.
Tak hanya swasta, enam unsur pemerintah turut digugat: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Gubernur Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Kementerian ESDM RI, Bupati Aceh Utara, serta PT Perkebunan Nusantara IV Regional VI. Mereka dituding lalai mengawasi dan melindungi lingkungan, sehingga perusakan berlangsung tanpa rem.
“Ini bukan sekadar gugatan,” kata Rius. “Ini peringatan.”
Bagi masyarakat Aceh Utara, perkara ini adalah garis batas. Antara pembangunan dan perampasan. Antara izin dan impunitas. Antara keuntungan dan nyawa.
Banjir sudah terjadi.
Kerusakan sudah nyata.
Kini pengadilan diuji: berpihak pada rakyat, atau membiarkan kejahatan lingkungan kembali disapu air. (SR/tim)