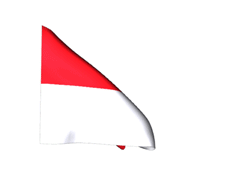Oleh: ER. K
Subulussalam, Aceh—Hari Jumat seharusnya membawa ketenangan, tetapi subuh di kota ini justru diwarnai oleh alarm keras yang mengguncang fondasi kebebasan. Insiden pengrusakan mobil dan intimidasi terhadap Syahbudin Padank, seorang jurnalis yang juga pengurus organisasi pers di Aceh, adalah pengkhianatan nyata terhadap janji reformasi dan semangat demokrasi kita.

Ini bukan sekadar kasus pidana pengrusakan barang—seperti yang diatur dalam Pasal 406 KUHP. Ini adalah serangan pengecut terhadap Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang Pers, yang menjamin hak wartawan untuk mencari, menyebarkan informasi, dan mendapat perlindungan hukum. Ketika kaca belakang mobil seorang jurnalis dipecahkan di tengah malam, itu adalah simbol bahwa pihak-pihak yang terusik oleh kebenaran mencoba memecahkan pilar keempat demokrasi: pers yang merdeka.
Ancaman dalam Senyap Subuh
Kronologi yang dilaporkan sungguh meresahkan. Dua sepeda motor tak dikenal mondar-mandir, knalpot digeber, klakson dipanjangkan secara provokatif. Ini bukan ulah iseng remaja, melainkan orkestrasi teror yang disengaja. Tujuannya tunggal: menanamkan ketakutan.
Dampak psikologisnya jauh melampaui kerugian material. Istri dan anak-anak Syahbudin kini merasakan kengerian di rumah sendiri, tempat yang seharusnya menjadi benteng perlindungan terakhir. Trauma yang dialami keluarga ini adalah harga yang harus dibayar oleh seorang jurnalis karena berani menyuarakan apa yang wajib diketahui publik.
Siapa pun yang melakukan teror ini, ia bukan hanya melawan Syahbudin Padank, tetapi menantang seluruh insan pers dan hak dasar setiap warga negara Indonesia.
Menguji Komitmen Negara
Ketua Serikat Siber Wartawan Indonesia (SWI) Subulussalam, Suhendri Solin, benar: ini adalah serangan terhadap seluruh wartawan. Jika kejahatan intimidasi seperti ini dibiarkan berlalu tanpa pengusutan tuntas, maka kita akan mengirim pesan yang berbahaya: bahwa UU Pers hanyalah kertas tanpa gigi, dan siapa pun yang punya kepentingan tersembunyi bisa membungkam suara kritis dengan kekerasan.
Oleh karena itu, sorotan kini tertuju pada lembaga-lembaga penegak hukum dan penjaga pilar demokrasi:
– Kapolres Subulussalam dan Kapolda Aceh: Masyarakat menantikan respons cepat dan serius. Penangkapan pelaku harus dilakukan segera, membuktikan bahwa hukum tidak tunduk pada kekuatan teror. Pengawasan langsung dari Kapolri menjadi keharusan agar kasus ini tidak menguap menjadi sekadar statistik.
– Dewan Pers: Lembaga ini harus mengambil peran advokasi aktif, memastikan Syahbudin Padank dan keluarganya mendapatkan perlindungan hukum dan psikologis. Insiden ini adalah momentum bagi Dewan Pers untuk menegaskan kembali otoritasnya di mata publik dan aparat.
– Komnas HAM dan LPSK: Dengan indikasi pelanggaran HAM yang nyata, termasuk perampasan rasa aman dan kebebasan berekspresi, kedua institusi ini wajib turun tangan. Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus segera mengevaluasi kebutuhan perlindungan bagi Syahbudin dan keluarganya.
Pasal 18 ayat (1) UU Pers secara tegas mengancam hukuman pidana dua tahun penjara atau denda hingga Rp500 juta bagi penghambat kemerdekaan pers. Pasal ini tidak boleh menjadi macan kertas. Kebebasan pers adalah oksigen bagi demokrasi; ketika oksigen disumbat, yang tercekik adalah seluruh rakyat.

Penutup: Jangan Biarkan Kaca yang Pecah Menjadi Tanda Titik
Di tengah gelombang kecaman dari LSM dan komunitas pers, kita diingatkan kembali: solidaritas adalah benteng terakhir jurnalis. Teror di Subulussalam bukan hanya soal selembar berita atau sebidang kaca mobil yang pecah, melainkan tentang apakah negara kita masih menjamin hak untuk mengatakan kebenaran tanpa ketakutan.
Jangan biarkan teror ini menjadi tanda titik bagi kebebasan pers di Subulussalam, atau di mana pun di Indonesia. Serangan terhadap seorang jurnalis adalah penghinaan terhadap cita-cita demokrasi. Negara harus hadir, hukum harus tegak, dan kebenaran harus menang. Lindungi Jurnalis. Lindungi Demokrasi.