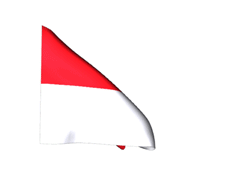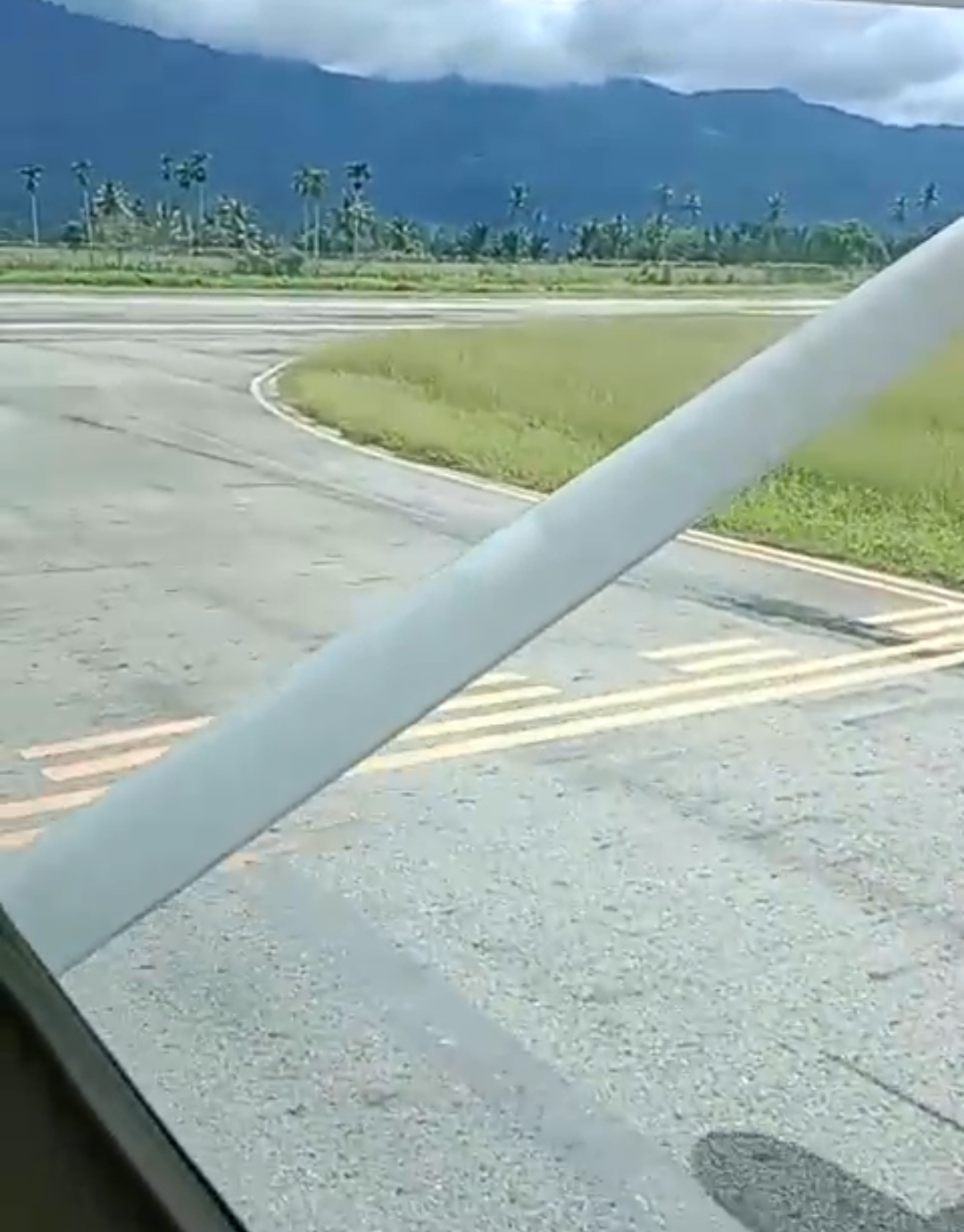Oleh: Arfi Ngah
Ada banyak cara mengenali watak seorang pemimpin. Sebagian memilih membaca rekam jejak kebijakan, sebagian lain menelisik pidato dan janji politiknya.
Namun sesekali, watak itu justru tampak paling jujur dalam peristiwa kecil yang nyaris luput dari sorotan. Subuh yang sunyi, jamaah yang sedikit, dan seorang kepala daerah yang berdiri di depan, memimpin shalat, tanpa kamera, tanpa kerumunan, tanpa tepuk tangan.
Pagi itu, Pendopo Bupati Gayo Lues tidak sedang menjadi pusat aktivitas resmi. Tidak ada agenda protokoler, tidak pula rombongan tamu besar. Yang terdengar hanya lantunan pengajian dari masjid-masjid sekitar, sebuah kebiasaan yang sudah menyatu dengan denyut Aceh setiap jelang Subuh.
Dalam suasana seperti itu, tubuh yang lelah setelah menempuh perjalanan panjang sejatinya punya banyak alasan untuk memilih tetap terlelap. Tetapi Subuh memang selalu menjadi ujian paling jujur tentang prioritas.
Shalat Subuh berjamaah di mushala pendopo itu berlangsung sederhana. Jamaahnya bisa dihitung dengan jari. Tidak lebih dari enam orang. Seorang ajudan, petugas pengamanan, dua personel Satpol PP yang tampaknya sedang piket, dan satu tamu yang kebetulan singgah.
Di hadapan mereka, berdiri seorang imam yang bukan ustaz tetap, bukan pula tokoh agama setempat, melainkan Bupati Gayo Lues sendiri, H. Muhammad Amru.
Pemandangan itu terasa ganjil sekaligus menenangkan. Ganjil, karena dalam realitas birokrasi hari ini, tidak banyak kepala daerah yang memulai hari dengan menjadi imam shalat bagi bawahannya. Menenangkan, karena di tengah riuh politik dan jabatan, masih ada pemimpin yang menempatkan dirinya sejajar dengan rakyat dan stafnya di hadapan Tuhan.
Jika ada yang tergesa menyebut peristiwa seperti ini sebagai pencitraan, logika sederhana segera membantahnya. Tidak ada kamera, tidak ada undangan, tidak ada publikasi. Jamaahnya terlalu sedikit untuk sebuah panggung politik.
Bahkan jika pun ingin membangun citra, tempat dan waktunya jelas bukan pilihan strategis. Subuh yang dingin di dataran tinggi Gayo Lues bukanlah ruang glamor untuk sebuah pertunjukan kekuasaan.
Justru di situlah maknanya terasa. Kepemimpinan, dalam wujud paling sunyi, kadang hadir bukan lewat pidato besar, melainkan lewat keteladanan yang nyaris tak disadari orang lain.
Bangun sebelum Subuh, berwudu dengan air dingin pegunungan, lalu berdiri memimpin shalat—itu bukan sekadar rutinitas ibadah, melainkan pesan diam bahwa jabatan tidak membebaskan seseorang dari disiplin spiritual.
Gayo Lues adalah daerah yang tidak ramah bagi tubuh malas. Udara dinginnya menuntut kesungguhan, bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Ketinggiannya yang mencapai ribuan meter di atas permukaan laut membuat pagi hari terasa menggigit.
Dalam konteks itu, kehadiran seorang bupati di mushala sebelum fajar adalah cerminan pilihan hidup: memilih bangun, ketika alasan untuk tetap tidur begitu berlimpah.
Tidak semua orang harus mengidolakan sosok tertentu. Tidak pula setiap pemimpin harus dipuja. Namun ada momen-momen tertentu yang pantas dicatat sebagai pengingat, bahwa kekuasaan tidak selalu menjauhkan seseorang dari nilai-nilai dasar.
Bahwa politik tidak selalu identik dengan jarak, privilese, dan kenyamanan berlebih.
Lima tahun masa jabatan H. Muhammad Amru sebagai Bupati Gayo Lues kini telah selesai. Sejarah tentu akan menilai kepemimpinannya dari berbagai sisi:
kebijakan, pembangunan, dan dinamika politik daerah. Tetapi bagi sebagian orang, kenangan tentang kepemimpinan justru melekat pada hal-hal kecil yang bersifat personal. Subuh yang hening itu menjadi salah satunya.
Di tengah kelelahan perjalanan, Subuh di mushala pendopo justru menyisakan kesegaran batin. Bukan semata karena berhasil mengejar jamaah, melainkan karena menyaksikan langsung bahwa kepemimpinan bisa hadir dengan cara yang sangat manusiawi. Tanpa jarak. Tanpa formalitas. Tanpa keharusan untuk terlihat.
Barangkali, begitulah seharusnya pemimpin dikenang: bukan hanya dari apa yang tertulis di laporan, tetapi dari keteladanan yang diam-diam membekas. Dan Subuh di Negeri Seribu Bukit itu, tanpa disadari, telah mengajarkan satu hal penting—bahwa memimpin bukan selalu soal berada di depan barisan, melainkan soal kesiapan berdiri paling awal ketika yang lain masih mencari alasan untuk bangun.