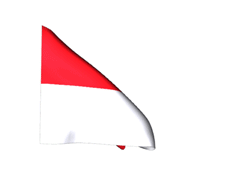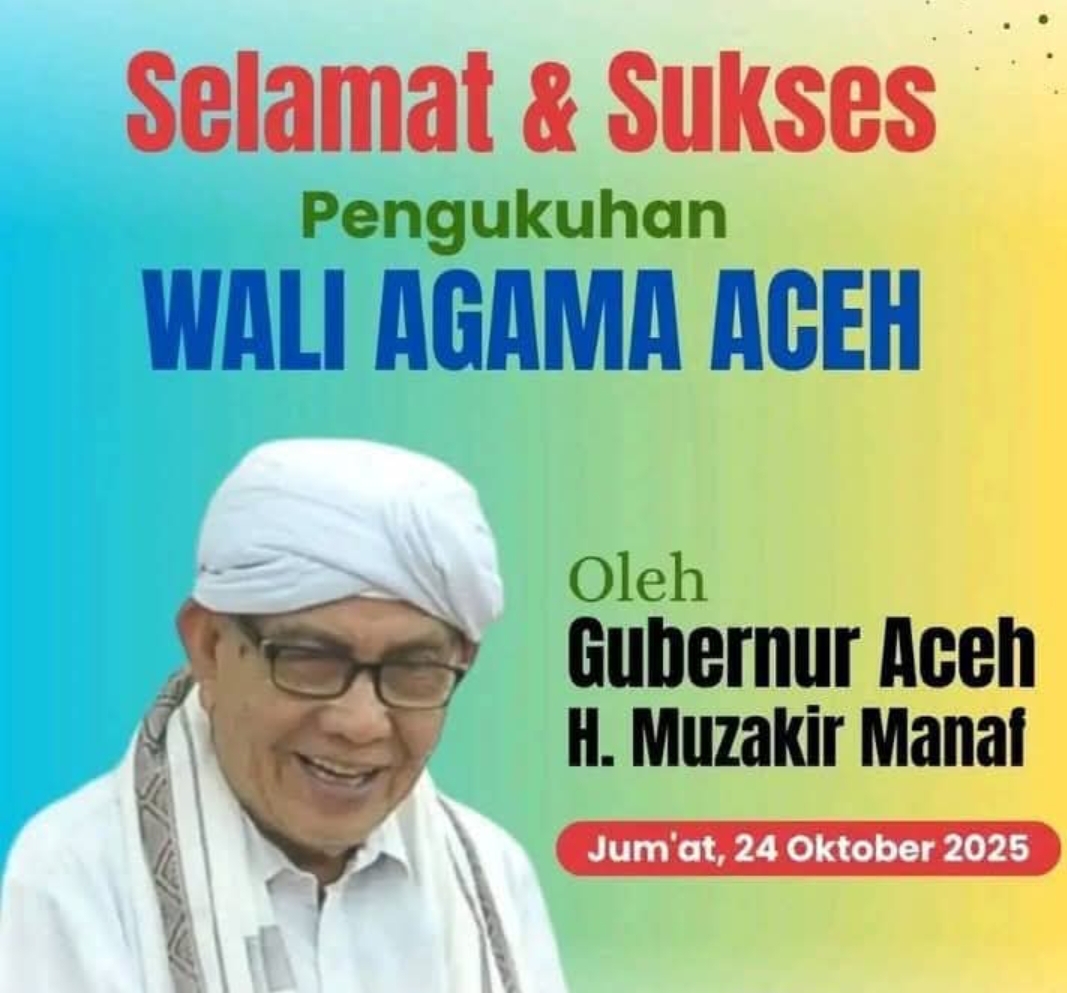Opini: Oleh Siwa Rimba
Di Aceh Utara, ironi bukan sekadar cerita—ia menjadi kenyataan sehari-hari. Di daerah yang sejak dekade 1970-an dibanggakan sebagai ladang gas raksasa, tabung elpiji 3 kilogram justru menjadi barang langka yang diburu seperti komoditas mewah. Setiap pekan, antrean panjang warga berjejal di pangkalan, membawa tabung kosong yang entah kapan bisa terisi. Di negeri gas, rakyat justru kehabisan napas.
Pemerintah daerah selalu punya jawaban standar: distribusi normal, kuota mencukupi, pantauan terus dilakukan. Pertamina pun senada. Namun di lapangan, tabung hijau bersubsidi itu hanya muncul dua jam, lalu lenyap seketika. Warga menelusuri kios demi kios, pulang dengan tangan hampa, sementara para pejabat tetap percaya pada laporan-laporan rapi yang tidak pernah mencerminkan kenyataan.
Siapa yang bermain? Pertanyaan itu menggantung setiap kali harga elpiji bersubsidi melambung dua kali lipat di gampong-gampong. Jika kuota cukup, mengapa tabung langka? Jika distribusi normal, mengapa warga selalu kalah cepat dari para “pengumpul dadakan” yang entah bekerja untuk siapa? Jika pemerintah mengawasi, mengapa permainan harga dibiarkan berlangsung bertahun-tahun?
Yang tak terbantahkan adalah satu fakta: kelangkaan ini bukan soal teknis, melainkan soal ketidakberesan tata kelola. Ada rantai distribusi yang bocor. Ada pangkalan yang sengaja “menghilangkan” stok. Ada agen yang bermain di balik layar. Dan ada pemerintah yang menutup mata, atau sekadar hadir saat krisis sudah meledak.
Semuanya menjadi lebih ironis ketika kita mengingat bahwa Aceh Utara hidup berdampingan dengan pusat industri gas nasional. Pipa-pipa raksasa menyalurkan energi ke luar provinsi, sementara warga setempat harus berebut tabung gas bersubsidi. Jika ini bukan penghinaan terhadap akal sehat, lalu apa?
Pemerintah daerah sering berbicara tentang “komitmen”, “pengawasan”, dan “penertiban”. Tapi kata-kata itu kehilangan makna ketika ibu rumah tangga harus menunggu berjam-jam di pangkalan, atau ketika pedagang kecil terpaksa menutup warung karena kompor tak bisa menyala. Krisis elpiji ini bukan sekadar kegagalan teknis; ini adalah cermin dari pemerintahan yang enggan memutus mata rantai permainan yang sudah lama dibiarkan tumbuh.
Aceh Utara tidak kekurangan gas. Yang kekurangan adalah keberpihakan pada rakyat. Selama pejabat lebih nyaman menerima laporan daripada melihat kenyataan, selama distribusi bersubsidi lebih menguntungkan sebagian kecil pemain, dan selama publik dibuat percaya bahwa kelangkaan adalah “hal biasa”, maka tragedi elpiji ini akan terus berulang—tahun demi tahun.
Di daerah penghasil gas, yang langka bukanlah elpiji.
Yang benar-benar langka adalah keberanian memutus lingkaran kemacetan yang sudah terlalu lama dicatat sebagai kelaziman.