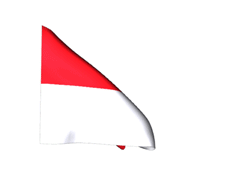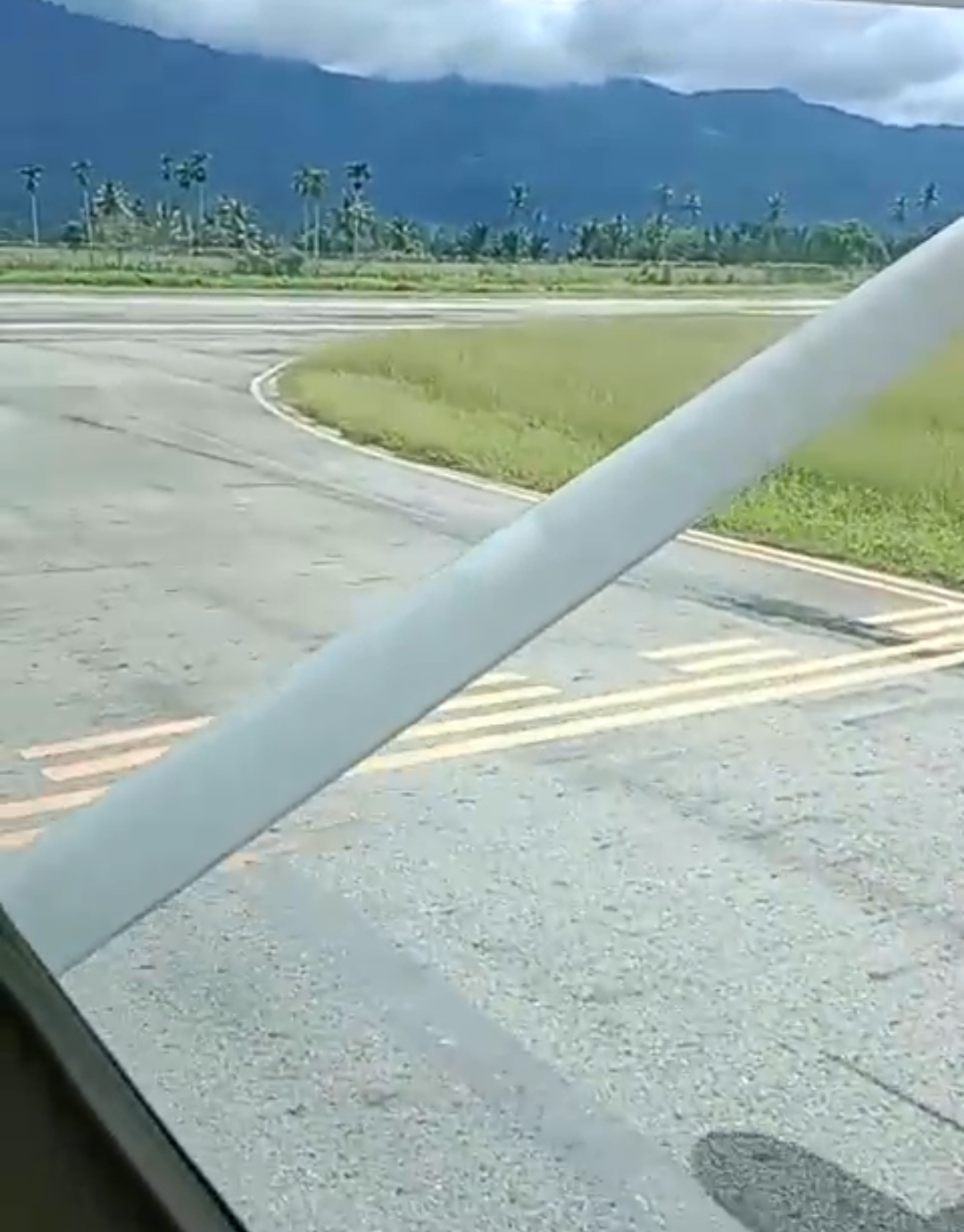Opini – Dua puluh tahun sudah Aceh menandatangani perjanjian damai yang mengakhiri konflik panjang dan penuh darah. Dentuman senjata digantikan riuh pasar, wajah-wajah pucat ketakutan berganti senyum anak-anak yang berlarian di jalan kampung. Namun, di balik potret damai itu, ada ironi yang tak pernah pudar: kesejahteraan dan ketimpangan masih menjadi selimut tebal yang menutupi mimpi rakyat Aceh.
Dana otonomi khusus yang mengalir triliunan rupiah tiap tahun seharusnya menjadi pengungkit ekonomi, membuka lapangan kerja, dan membangun infrastruktur yang layak. Namun, fakta di lapangan menunjukkan jurang kesenjangan yang menganga.
Ditengah gedung-gedung pemerintahan yang megah, masih banyak desa yang akses jalan rusak dan terputus, sekolah dengan fasilitas yang kurang memadai, fasilitas kesehatan yang jauh dari kesempurnaan, dan deretan rumah reot masyarakat miiskin yang tak layak huni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironi semakin terasa ketika laporan resmi menunjukkan angka kemiskinan Aceh bertahan di papan atas nasional. Banyak keluarga masih hidup dari hasil tani subsisten, nelayan bergantung pada laut yang tak lagi ramah, dan generasi muda merantau karena lapangan kerja di tanah sendiri semakin sempit.
Dua dekade damai seharusnya cukup waktu untuk menata fondasi kesejahteraan. Namun, yang terlihat justru birokrasi gemuk, elite politik yang sibuk berbagi kursi, dan kebijakan yang lebih sering memanjakan kelompok tertentu ketimbang mensejahterakan rakyat secara merata.
Damai tanpa keadilan sosial hanyalah ketenangan semu ibarat luka yang tertutup kulit, namun membusuk di dalam.
Kini, Aceh dihadapkan pada pertanyaan yang tak bisa lagi dihindari: apakah damai ini akan kita biarkan menjadi monumen tanpa makna, atau kita jadikan tonggak untuk menghapus ketimpangan?
Dua dekade sudah terlewati. Rakyat Aceh tak hanya ingin hidup tanpa konflik, mereka ingin hidup dengan martabat, kesejahteraan, dan kesempatan yang setara.
Penulis: Siwah Rimba