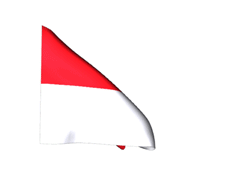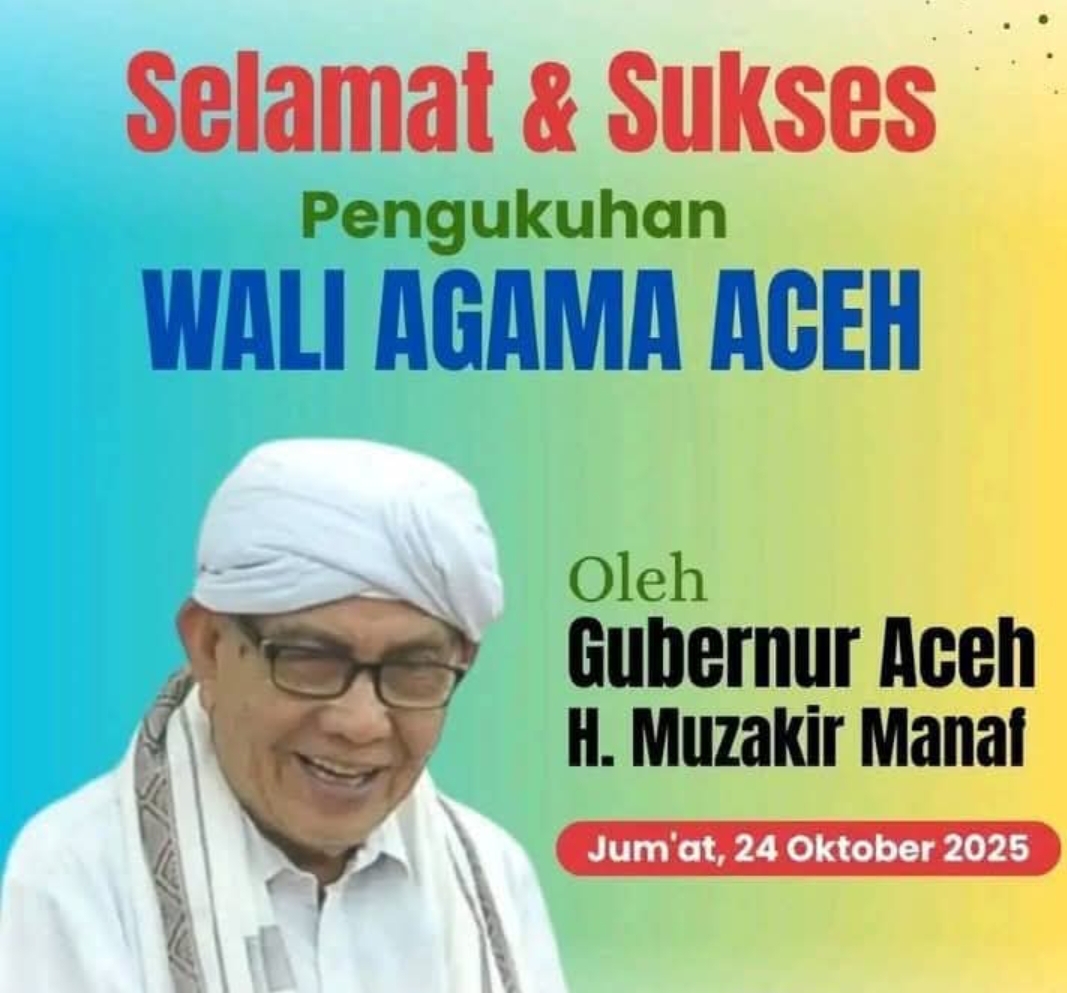Subulussalam – Kebijakan sepihak PT Lotbangko menuai bara di Subulussalam. Setelah bertahun-tahun menjadi urat nadi penghubung warga ke lahan pertanian, akses jalan di Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, kini ‘disandera’ portal besi.
Ironisnya, penutupan ini terjadi setelah Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut diperpanjang, sebuah aksi yang terang-terangan menelikung hak-hak publik yang dijamin undang-undang.
Keresahan warga Kota Subulussalam mencapai puncaknya.

Jalan yang telah dihibahkan untuk kepentingan masyarakat—bahkan pernah menjadi aspirasi resmi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam—kini berubah menjadi dinding penghalang.
PT Lotbangko, yang HGU-nya berakhir pada 2019 dan kembali diperpanjang pada 2021, justru memilih jalur konfrontasi dengan menutup akses vital tersebut.
Sejak perpanjangan HGU disahkan, aktivitas berkebun warga kerap tertahan di gerbang besi. P. Siburian, salah seorang warga yang hendak melintas, membenarkan perlakuan ini.
“Saya sempat dilarang oleh sekuriti dan akhirnya terpaksa berbalik arah. Tidak jadi ke kebun,” ujarnya, menggambarkan betapa rentannya posisi warga di hadapan penguasa lahan korporasi.
Tindakan PT Lotbangko ini disorot tajam karena secara jelas mengangkangi sejumlah pasal krusial dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Regulasi ini secara eksplisit memuat kewajiban pelaku usaha perkebunan untuk mengutamakan kepentingan umum dan sosial, antara lain:
Pasal 9 ayat (2) yang mewajibkan pemberian akses terhadap kepentingan umum; Pasal 15 yang menekankan perhatian terhadap kepentingan masyarakat sekitar; dan Pasal 58 ayat (1) yang secara spesifik mewajibkan pemberian akses jalan kepada masyarakat yang lahannya terkurung di dalam areal perkebunan.
Ketiga pasal ini adalah pilar yang seharusnya menopang koeksistensi antara perusahaan dan masyarakat. Namun, PT Lotbangko dinilai telah menjadikan undang-undang hanya sebatas kertas kerja, bukan pedoman operasional yang mengikat.
Penutupan akses ini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi warga, tetapi juga secara fundamental merampas hak mereka atas jalan yang sudah lama ada.

Masyarakat kini berharap penuh pada Pemerintah Daerah dan instansi terkait di Subulussalam. Mereka mendesak agar otoritas segera mengambil langkah tegas. Ini bukan hanya soal membuka portal, tetapi soal menegakkan supremasi hukum dan memastikan kedaulatan warga atas lahan dan akses mereka.
Jika arogansi korporat dibiarkan, preseden buruk ini akan menjadi ancaman bagi masyarakat lain yang hidup berdampingan dengan industri perkebunan.
Kasus Namo Buaya adalah cermin buram praktik bisnis yang buta sosial dan tuli hukum, menuntut intervensi cepat sebelum konflik ini memanas menjadi gejolak yang lebih besar.
Mampukah pemerintah menjadi arsitek keadilan yang membongkar tembok arogansi korporat ini, ataukah hak warga akan terus terkubur di bawah payung HGU yang diperpanjang? Taruhannya adalah kredibilitas negara dalam menjamin hak dasar rakyatnya. [Parlindungan]