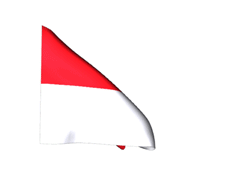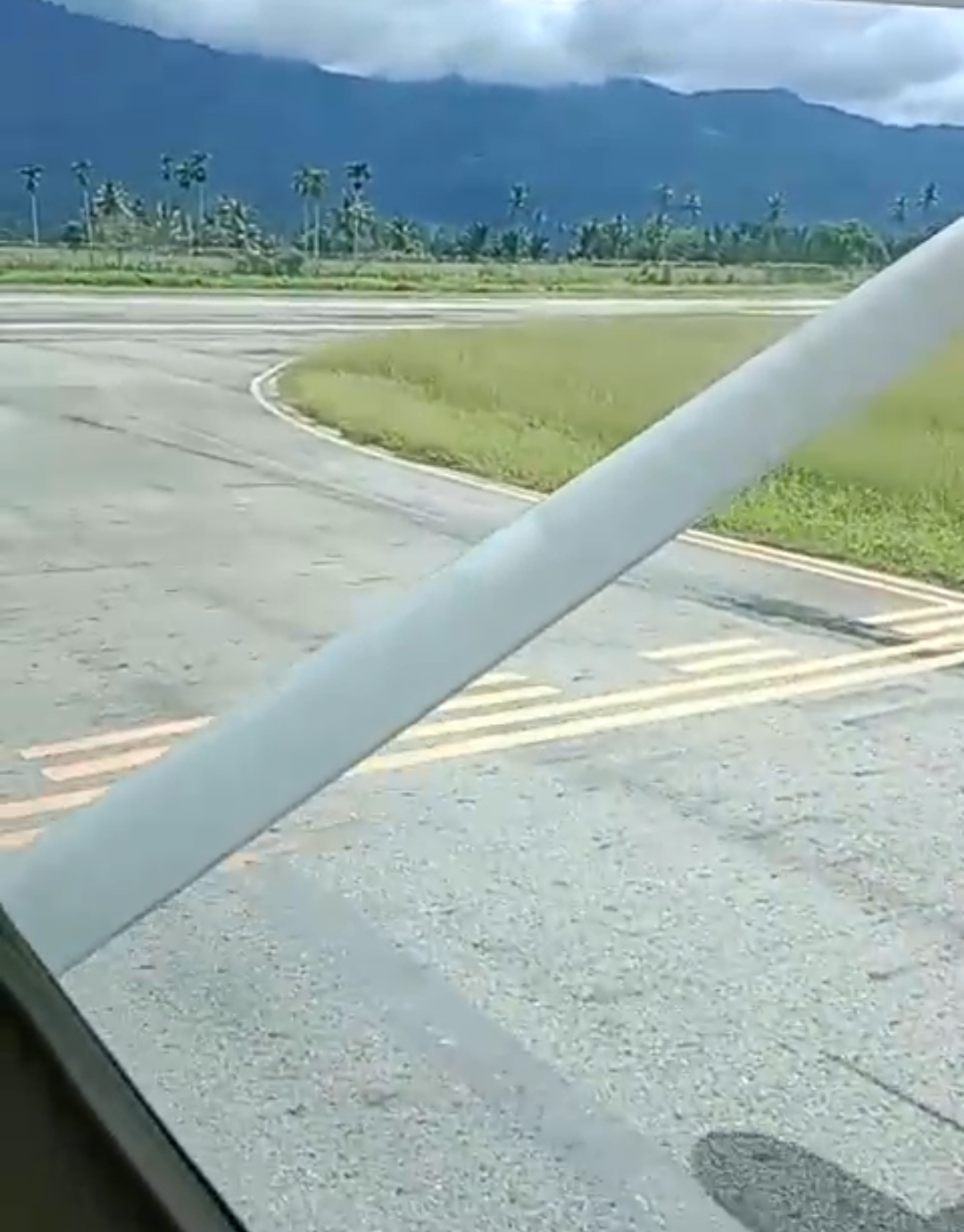Aceh — Pemerintah dinilai piawai memanfaatkan kerja wartawan saat bencana, tetapi kerap menutup mata ketika para jurnalis itu sendiri terjerembap dalam musibah.
Kritik keras itu disampaikan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyusul banjir yang melumpuhkan kerja puluhan wartawan di berbagai daerah Aceh.
Banjir yang merendam Aceh Utara, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Bireuen, Pidie Jaya, hingga Lhokseumawe tak hanya menghanyutkan rumah dan harta warga.
Di balik liputan yang ramai di layar gawai, sejumlah wartawan kehilangan alat kerja—kamera dan laptop—yang rusak terendam air. Tanpa itu, profesi mereka lumpuh total.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua YARA Aceh Barat, Hamdani, S.Sos., S.H., M.H., menyebut kondisi ini sebagai potret telanjang relasi timpang antara pemerintah dan jurnalis.
“Ketika bencana datang, wartawan dikejar-kejar untuk meliput. Saat mereka sendiri jadi korban, pemerintah mendadak tuli dan buta,” kata Hamdani, Rabu, 21 Januari 2026.
Menurut dia, pemerintah selama ini menikmati limpahan manfaat dari pemberitaan bencana—mulai dari legitimasi, simpati publik, hingga citra kepedulian.
Namun, tidak ada mekanisme perlindungan ketika jurnalis kehilangan alat produksi yang menjadi satu-satunya sumber penghidupan.
“Negara ingin berita, tapi enggan menanggung risiko yang dipikul pembuat berita,” ujar Hamdani.
YARA menilai pengabaian ini berbahaya. Tanpa alat kerja, wartawan tak bisa meliput. Tanpa liputan, suara korban akan senyap. Dalam situasi darurat, itu berarti matinya fungsi kontrol dan informasi publik.
Atas dasar itu, YARA mendesak pemerintah segera melakukan pendataan khusus wartawan terdampak, menyediakan bantuan konkret untuk penggantian alat kerja, serta menghentikan cara pandang yang menempatkan jurnalis sebatas instrumen pencitraan kekuasaan.
“Jangan hanya ingat wartawan saat butuh panggung. Jika negara terus abai, yang dipertaruhkan bukan cuma nasib jurnalis, tapi hak publik atas informasi,” kata Hamdani. [SR/Tim]