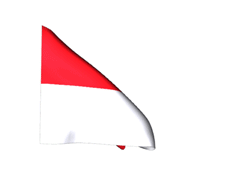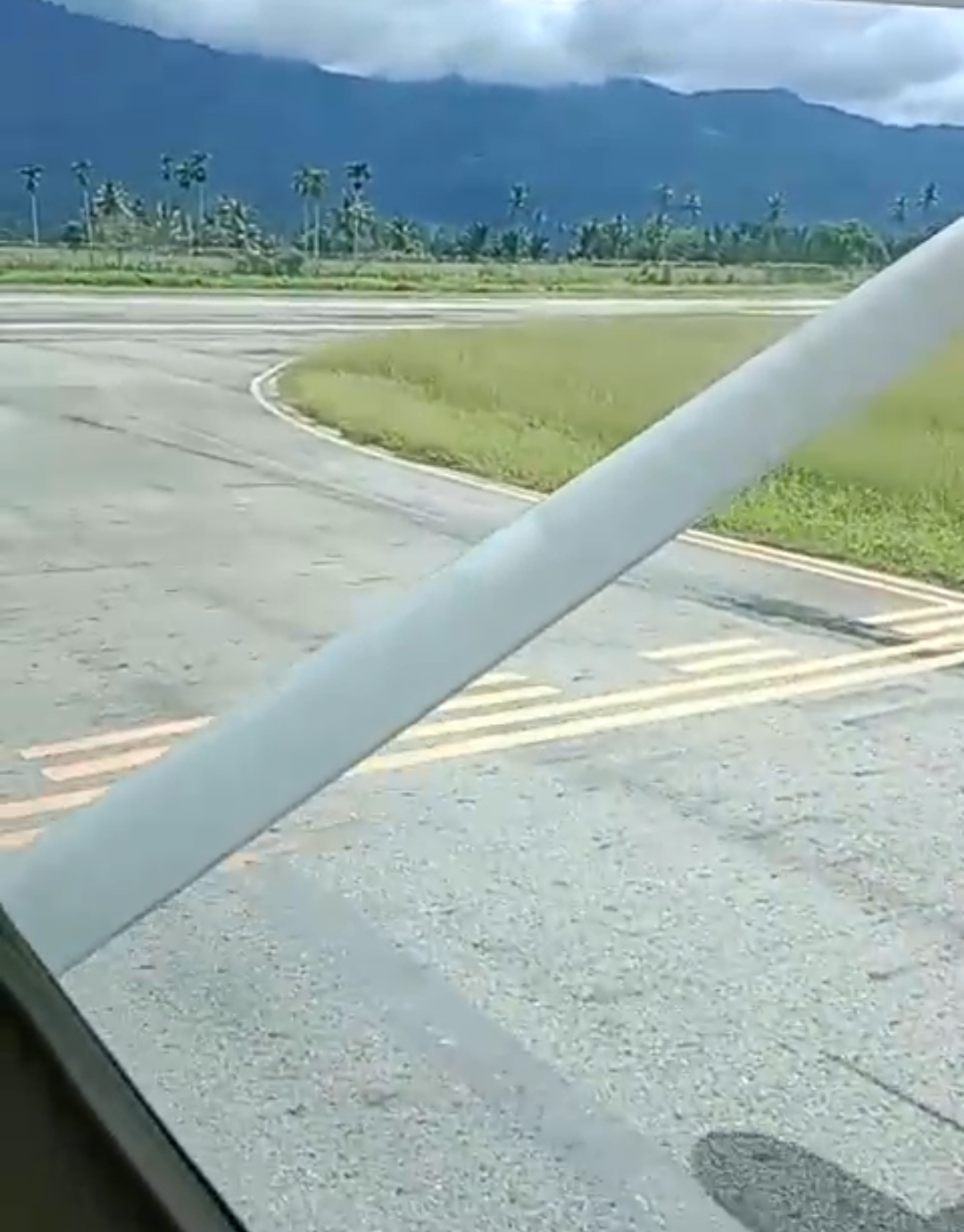Mantan Wartawan Serambi Tahun 90 an, H. Muhammad Amru,bersama Ketua Umum PWI Terpilih Akhmad Munir di jakarta baru- baru ini.
Jakarta – Rekonsiliasi yang terjadi di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bukan hanya sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan sebuah studi kasus tentang dinamika kekuasaan, etika profesi, dan peran media dalam sebuah negara.
Setelah dua tahun dilanda perpecahan yang menggerogoti kredibilitasnya, terpilihnya Akhmad Munir dan Atal S. Depari melalui Kongres Persatuan di Cikarang, Bekasi, pada 29-30 Agustus 2025, menjadi titik balik yang menarik untuk dikaji.
Dualisme kepemimpinan PWI yang melibatkan dua kubu, yakni hasil Kongres Bandung 2023 dan Kongres Luar Biasa (KLB) Jakarta 2024, bukan fenomena baru.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat berbincang- bincang dengan Ketua Umum PWI terpilih Akhmad Munir.
Perpecahan ini, menurut beberapa pengamat, merupakan puncak dari akumulasi masalah internal yang sudah lama membusuk, mulai dari isu transparansi keuangan, dugaan politisasi organisasi, hingga konflik kepentingan.
PWI, sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia, seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga independensi pers, namun justru terjebak dalam pusaran konflik internal. Kondisi ini membuat PWI kehilangan daya tawar dan legitimasi di mata publik dan pemerintah.
Intervensi dan peran Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam memfasilitasi rekonsiliasi ini menunjukkan betapa krusialnya peran PWI bagi stabilitas informasi nasional.
Menkomdigi secara eksplisit meminta pengurus baru untuk merangkul kembali Hendry Ch. Bangun, sebuah langkah yang menandakan pentingnya rekonsiliasi sejati—bukan sekadar formalitas.
Keputusan ini, jika diimplementasikan dengan tulus, bisa menjadi preseden positif bagi organisasi-organisasi profesi lainnya yang juga menghadapi perpecahan.
Meskipun kesepakatan sudah tercapai, jalan di depan tidak akan mulus. Akhmad Munir dan timnya menghadapi tiga tantangan utama. Pertama, tantangan internal. Mengintegrasikan kembali anggota dan pengurus dari dua kubu yang sempat berseteru membutuhkan lebih dari sekadar penempatan nama dalam struktur organisasi.

Diperlukan dialog, transparansi, dan komitmen bersama untuk melupakan friksi masa lalu. Kegagalan dalam mengelola dinamika internal ini bisa memicu perpecahan baru di masa depan.
Kedua, tantangan etika profesi. Di tengah arus informasi yang kian masif dan cepat, PWI harus kembali ke akarnya sebagai penjaga kode etik jurnalistik. Kasus-kasus pelanggaran etika yang melibatkan anggota PWI harus ditangani secara tegas dan transparan.
Organisasi ini harus membuktikan bahwa mereka mampu menjadi benteng terakhir yang menjaga martabat dan profesionalisme wartawan.
Ketiga, tantangan disrupsi digital. Teknologi telah mengubah lanskap media secara fundamental.
Jurnalisme konvensional menghadapi ancaman dari kecerdasan buatan (AI), media sosial, dan platform berita yang tidak terverifikasi. PWI harus berinovasi, tidak hanya dalam pelatihan bagi anggotanya, tetapi juga dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan ekosistem media saat ini.
Kolaborasi dengan pemerintah, seperti yang ditekankan oleh Menkomdigi, menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini.
Rencana pelantikan pengurus di Museum Pers Nasional di Solo pada akhir September mendatang bukan sekadar pilihan lokasi, melainkan sebuah pernyataan. Museum ini adalah saksi bisu perjuangan pers nasional.
Dengan melangsungkan pelantikan di sana, PWI seolah ingin mengingatkan kembali seluruh anggotanya tentang sejarah dan misi luhur yang diemban: menjadi pilar keempat demokrasi yang bertanggung jawab dan berintegritas.
Masa depan PWI akan ditentukan oleh seberapa baik mereka menanggapi ketiga tantangan ini.
Apakah rekonsiliasi ini akan menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun kembali PWI yang profesional dan berintegritas, ataukah hanya akan menjadi jeda singkat sebelum krisis lain muncul? Waktu yang akan menjawab. []